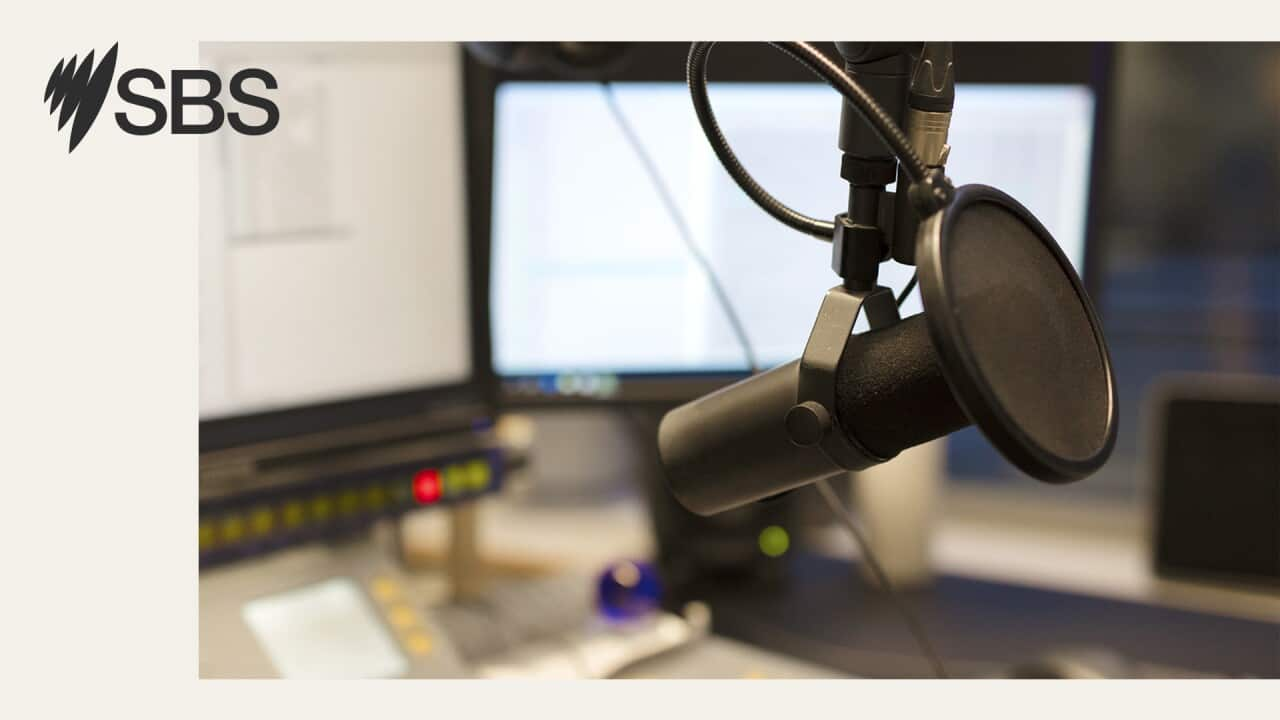Tanaman sawit sering sekali disebut sebagai salah satu faktor dominan penyebab bencana yang terjadi di pulau Sumatra beberapa waktu terakhir. Sejumlah ahli mengatakan bahwa sawit atau kebun sawit adalah sumber dari malapetaka ini karena tanaman monokultur ini merusak tanah yang pada gilirannya tidak mampu menahan air dan menyebabkan banjir besar.
Namun, petani sawit menolak klaim itu. Salah satu penolakan disampaikan oleh Misngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Riau, yang juga seorang petani sawit,
Menurut dia, bukan sawit yang merusak lingkungan, tetapi aksi korporasi lah penyebab utamanya.
Petani sawit, kata Misngadi, maksimal hanya mengolah beberapa hektar tanah. Sementara korporasi bisa memiliki ribuan, bahkan puluhan ribu hektar. Lahan itu, diperoleh pihak korporasi antara lain dengan menyerobot lahan hutan. Inilah sumber bencana itu.
Faktor kedua, menurut Misngadi, adalah konversi hutan menjadi hutan tanaman industri. Hutan alami, yang sebelumnya tersusun dari bermacam pohon, diubah menjadi hutan untuk keperluan industri dengan hanya satu macam pohon. Semua langkah korporasi itu, membabat habis hutan di Indonesia. Hutan tanaman industri adalah hutan yang betul-betul monokultur. Setiap lima tahun sekali, lahan diolah sedemikian rupa setelah panen kayu, sehingga kerusahan tanah menjadi-jadi. Ketika musim hujan datang, tanah itu tidak mampu lagi menahan air. Pola semacam inilah yang mengubah struktur tanah.
Petani sawit mandiri, yang mengelola lahan dalam luasan kecil, tahu praktik-praktik buruk korporasi sawit dalam mencaplok lahan. Misngadi memberi contoh, banyak lahan kecil-kecil dalam jumlah banyak diatasnamakan petani mandiri, padahal sebenarnya itu dikelola secara tidak langsung oleh korporasi. Praktik semacam itu banyak diterapkan, terutama untuk memperluas kawasan tanaman sawit di kawasan-kawasan terlarang, seperti hutan konservasi.
Misngadi mengatakan, jika memang negara itu betul-betul mengalokasikan 30% lahan tetap dalam kawasan hutan di dalam satu wilayah atau lokasi, dan dengan tata kelola yang bagus, bencana itu bisa diminimalkan risikonya.
Karena itu, tudingan pertama kali harus diarahkan ke korporasi sawit, bukan ke sawit sebagai tanaman. Petani sawit mandiri yang mengelola lahan sangat kecil, tidak bisa disamakan perannya dengan korporasi yang memiliki puluhan ribu hektar lahan.
Selain itu, petani sawit mandiri juga mengolah lahannya secara lebih ramah lingkungan, karena tidak sepenuhnya monokultur. Petani sawit mandiri hanya memiliki lahan di satu tempat, dan sebagai satu-satunya aset, lahan itu akan dimaksimalkan produksinya. Petani seperti Misngadi, kerap menanam pisang, nangka, jengkol, hingga merica di sela-sela tanaman sawit. Upaya itu disesuaikan dengan umur tanaman sawit itu sendiri, karena bisa mempengaruhi produktivitasnya.
Selain itu, petani sawit mandiri juga kerap menggunakan pupuk alam, berbeda dengan korporasi yang sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia. Misngadi meyakinkan, strategi ini jauh lebih ramah lingkungan.
Lepas dari perdebatan yang mengemuka, Misngadi mengaku, bencana Sumatera kali ini tetap harus menjadi titik balik perenungan bagi semua pihak. Sebagai petani, dia mendukung dilakukannya evaluasi kebijakan dan penindakan hukum secara tegas. Sayang, menurut dia, pemerintah saat ini belum melakukan itu.
Mengenai ekspansi sawit yang terus dilakukan, Misngadi juga menilai langkah itu tidak perlu. Produksi sawit Indonesia sudah berlebih, dan pembatasan produksi akan menjaga harga sawit. Selain itu, Serikat Petani juga merekomendasikan pola kerja sama yang lebih baik, sehingga korporasi besar tidak harus mengelola lahan sawit. Pengelolaan lahan cukup diberikan kepada petani, sehingga investasi korporasi lebih ditujukan pada produksi. Pola semacam ini, kata dia, akan menguntungkan semua pihak, termasuk membuat sawit Indonesia lebih ramah lingkungan.
Dengarkan podcast ini selengkapnya dan dengarkan laporan lainnya dari tanah air di sini.